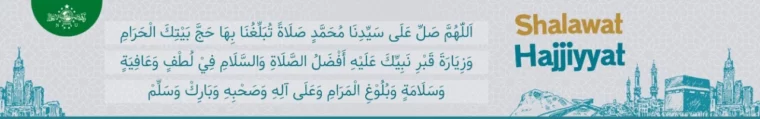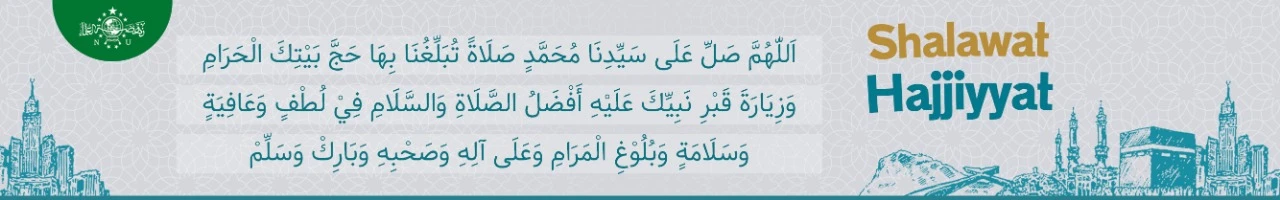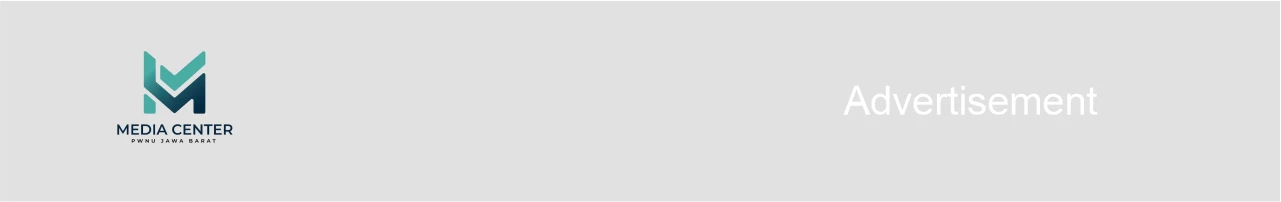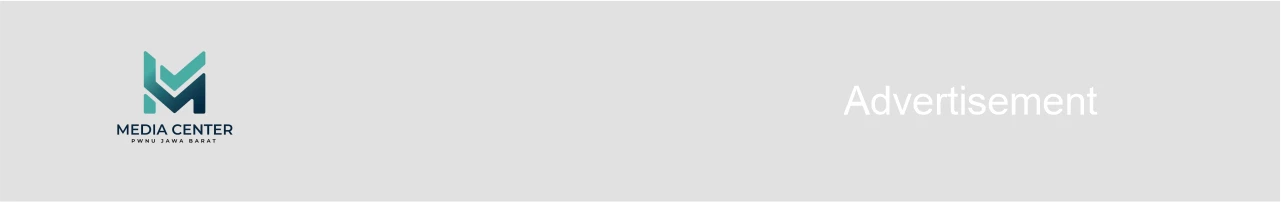Media NU sudah ada sejak masa-masa awal organisasi ini berdiri, seperti “Swara Nahdlatoel Oelama” (1927), “Oetoesan Nahdlatoel Oelama” (1928), “Berita Nahdlatoel Oelama” (1931), dan lainnya. Umumnya berbentuk majalah. Apa yang ada di benak para muassis NU ketika membangun media massa di era prakemerdekaan itu?
Saya kira media NU kala itu lebih dari sekadar menjalankan fungsi saluran komunikasi organisasi. Selain menunjukkan kesadaran pers yang cukup kuat di kalangan kiai pesantren, kehadiran media resmi adalah simbol otonomi di bidang informasi. Ulama kita waktu itu sadar akan kepungan propaganda yang bersebrangan dengan prinsip NU, termasuk dari media kaum kolonialis. Artinya, pendirian media juga bersifat ideologis. NU menghendaki kedaulatan informasi. Tidak sekadar jadi konsumen tetapi juga produsen. Bahasa santri sekarang: tak hanya sebagai maf’ul (objek informasi) tetapi juga fa’il (subjek informasi).
Begitu juga surat kabar, tabloid, dan majalah yang datang setelahnya, seperti Harian Duta Masjarakat, Soeara ANO (Ansoru Nahdlatil Ulama), Aula, Risalah, dll. Semuanya mencerminkan semangat NU yang menghendaki kemandirian di bidang informasi, minimal untuk warga NU sendiri.
Ketika internet mulai merangkak naik di Indonesia tahun 2000-an, PBNU era kepemimpinan KH Hasyim Muzadi mendirikan NU Online. Lagi-lagi, ini merupakan ikhtiar mengimbangi derasnya informasi, dalam konteks ini lewat pintu dunia maya. Tentu pada tahun 2003-an itu jumlah pengaksesnya sangat kecil. Kesadaran berinternet masyarakat Indonesia masih minim sekali, apalagi warga NU yang memang terkenal selalu tertinggal soal teknologi. Ormas Islam yang memiliki situs web pun saya kira juga masih bisa dihitung jari satu tangan.
Menurut cerita para senior, pengunjung terbanyak NU Online disinyalir datang dari kelompok Salafi dkk. Bukan untuk “membaca” artikel NU Online, melainkan melancarkan “serangan-serangan” di kolom komentar dan forum diskusi yang tersedia di web. Dikatakan “terbanyak” karena nyaris tidak ada warga NU lain yang memukul balik serangan melalui komentar sejenis. Redaksi cukup kuwalahan memoderasi, hingga akhirnya fitur interaksi itu pun ditiadakan. Adanya “pasukan siber” ini cukup mengindikasikan bawah kelompok Salafi memang selangkah lebih melek dari Nahdliyyin di bidang teknologi dan informasi.
Dugaan ini diperkuat ketika dalam kurun sepuluh tahun berikutnya kelompok itu betul-betul mendominasi jagat internet. Platform mesin telusur seperti Google dan Yahoo hampir selalu merekomendasikan web-web ultrakonservatif (sebagian bahkan ektremis) untuk kata kunci keislaman. Dulu, dengan hanya mengetik “Gus Dur” di Google, secara otomatis muncul rekomendasi “Gus Dur dibaptis”, “Gus Dur murtad”, dst. Begitu juga kata kunci tahlil, negara Islam, khilafah, jihad, dll—nyarisbtidak ada konten penyeimbang yang muncul di mesin pencarian. Klaim NU adalah kelompok mayoritas hanya berlaku di dunia nyata. Tidak di dunia maya.
Transformasi
Pasca-Muktamar Jombang (2015), NU Online mulai memperkuat strategi. Kedaulatan informasi tidak cukup untuk warga NU semata, melainkan umat Islam Indonesia secara umum. Lalu lintas konten internet masa kini adalah isi kepala masyarakat Indonesia di masa depan. Dengan demikian, NU Online mau tidak mau mesti bertransformasi dari karakter media ormas menjadi media keislaman; dari sekadar menjalankan fungsi kehumasan menjadi pusat informasi belajar tentang Islam. Instrumennya tak lagi cuma situs web tetapi juga media sosial di berbagai platform (YouTube, FB, IG, Twitter, Helo, Spotify, TikTok, dan nanti entah apalagi). Perluasan NU Online menjadi media multi-platform ini juga kian melejitkan trafik kunjungan hingga menduduki peringkat pertama untuk kategori media keislaman di Indonesia.
Sudah cukup? Ternyata belum. Tantangan juga datang media sosial itu sendiri. Akun-akun di luar NU rupanya sudah lebih dulu membesar. Artinya, akun NU juga mesti mengejar ketertinggalan. Belum lagi algoritma platform medsos kadang tidak ramah dengan kata kunci tertentu.
Ikhtiarnya, NU Online meluncurkan aplikasi super (super app) pada 2021 lalu. Dengan demikian, di luar instal TikTok atau Instagram, warga NU kini punya platform “sendiri”. Bedanya, NU Online Super App bukanlah medsos, melainkan aplikasi ibadah dan belajar Islam yang terdiri dari sekitar 20 fitur. Namun, setidkanya ia sedikit memenuhi tren ambisi masyarakat digital saat ini yang menghendaki “semuanya dalam satu genggaman” (https://nu.or.id/superapp). Proses penyempurnaan akan selalu dilakukan.
Ketua Umum Gus Yahya berulang kali mengatakan bahwa NU Online harus menjadi pusat digitalnya NU. Artinya, proyeksi ke depan, aplikasi ini lebih dari sekadar fasilitas ibadah dan belajar Islam tapi juga mendukung kerja-kerja organisasi, proses kadersasi, pengembangan UMKM, kesehatan, crowdfunding, dll. Nama “super app” yang sejak awal memang dimaksudkan sebagai doa diharapkan pada akhirnya akan menemukan wujud utuhnya.
Tentu itu semua baru langkah kecil. Masih banyak pekerjaan yang mesti diselesaikan. Ke depan kita masih dihadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan baru, seperti hadirnya Metaverse, yang diprediksi bakal mendisrupsi banyak kemapanan.
Idealnya, memang NU mesti menjadi raksasa teknologi itu sendiri untuk benar-benar berdaulat secara kaaffah. Jika berdaulat dari sisi konten sudah bisa, tugas berikutnya adalah berdaulat secara teknologi. Tentu ini proyek mahaberat. Sebagian mungkin bilang mustahil. Tapi, bukankah NU sudah biasa mengatasi perkara-perkara mustahil? (Mahbib Khoiron, …NU Online)
Mahbib Khoiron, jurnalis NU, opini pribadi dan tidak mewakili lembaga.
https://jabar.nu.or.id/ngalogat/cita-cita-daulat-digital-nu-zg4kY