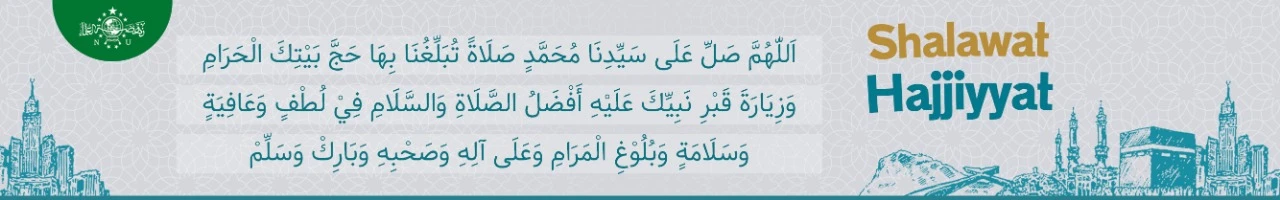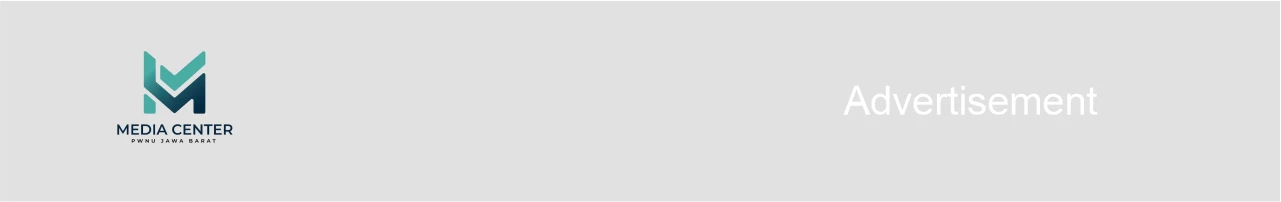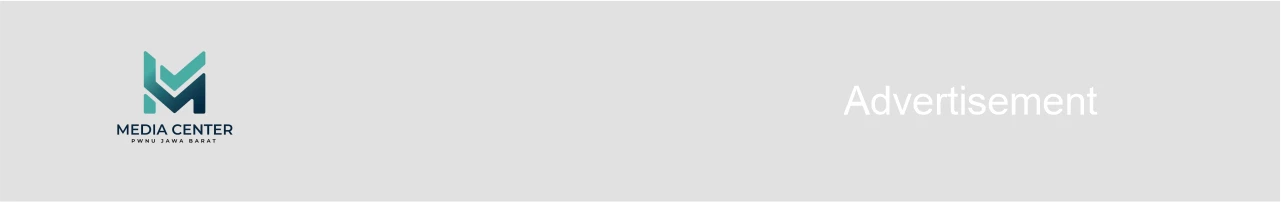“Ingin bahagia itu kan cita-cita. Merasa bahagia, senang dan dihormati.”
Itulah harapan Giwan, seorang penghayat Sunda Wiwitan berusia 18 tahun dari Kuningan, Jawa Barat. Sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), sebagai penghayat Giwan sudah merasa dibedakan. Tinggal di lingkungan yang mayoritas beragama muslim, Giwan kecil acap kali mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Karena berbeda agama, menyebabkan ia mengalami diskriminasi.
“Kenapa sih gak muslim aja?” Kalimat tersebut kerap ditunjukkan kepadanya saat itu. “Terus sama saya teh ‘kenapa kamu gak ke saya (Sunda Wiwitan) aja gitu?’ Dia nyewot dan (kami) berantem, karena dia yang mulai duluan mukul” kisah Giwan mengingat masa ketika SD.
Setidaknya Giwan sudah dua kali terlibat perkelahian, selebihnya adalah sindiran-sindiran yang dialamatkan kepadanya. Setelah Lulus SD, Giwan memutuskan bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tri Mulya, sekolah swasta yang dikelola oleh masyarakat penghayat Sunda Wiwitan, di Desa Cigugur, Kuningan. Bersekolah sejak SMP hingga sekarang duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memberikan ruang aman Giwan sebagai penghayat. Di lingkungan sekolah, terutama di SMP Tri Mulya, meski minoritas, ia pun merasa tidak menjadi minoritas.
“Hidup di Kuningan biasa aja, karena di Kuningan agamanya banyak. Jadi disebut minoritas enggak, tapi jika di Cikijing (penghayat Sunda Wiwitan) minoritas, karena kebanyakan muslim,” ujar remaja yang tengah menempuh pendidikan di SMK 1 Kuningan ini.
Ia beruntung karena sebagai penghayat di sekolah tidak mendapatkan diskriminasi dari teman-teman seperti halnya saat di SD. Bahkan selama di SMK, lanjut Giwan, guru-guru menghormatinya sebagai penghayat.
Saat awal masuk sekolah menyebutkan berasal dari Tri Mulya, hampir kebanyakan tahu bahwa ia beragama Sunda Wiwitan.
Kuningan memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Namun diakuinya di sekolah ia dikenal sosok yang lumayan pendiam. Giwan lebih suka mendengarkan orang lain dibandingkan membuka diri. Namun begitu, beberapa kali Giwan mendapatkan gelar juara Pencak Silat dan membuktikan bahwa sebagai penghayat ia mampu berprestasi.
Sunda Wiwitan Cigugur
Penghayat Sunda Wiwitan Cigugur merupakan kepercayaan lokal yang ajarannya mengikuti nilai nilai tradisi leluhur. Jejak sejarah Sunda Wiwitan hingga saat ini dapat dilihat melalui situs cagar budaya Paseban Tri Panca Tunggal yang telah ada sejak tahun 1840 dan hingga sekarang masih digunakan untuk kegiatan masyarakat adat.
Sunda Wiwitan dalam bingkai masyarakat awam diasosiasikan sebagai masyarakat yang sederhana, tinggal di pegunungan, eksklusif, menjaga hutan dan terbelakang.
“Jauh dari itu Sunda Wiwitan merupakan masyarakat yang memiliki semboyan ngaindung ka waktu nga bapak ka zaman, masyarakat Sunda Wiwitan mengikuti perubahan zaman” ujar Djuwita selaku salah satu keturunan pangeran Rama Djati
Menurutnya istilah tersebut memiliki arti bahwa penghayat bukan harus mengungkung diri dalam ke kolotan melainkan menerapkan nilai-nilai luhur dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanannya tradisi nilai adat terus beregenerasi mengikuti perkembangan zaman misalnya melanjutkan keyakinan leluhur yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
Menjadi masyarakat adalah pilihan mereka meneguhkan diri untuk melanjutkan apa yang sudah diwariskan leluhurnya. Pandangan orang-orang sudah subjektif terhadap nilai Sunda Wiwitan sehingga adanya pembunuhan karakter terhadap leluhur masyarakat adat. Sehingga masyarakat adat digambarkan sebagai orang mistik, klenik dan lain sebagainya.
“Di luar dari itu penghayat Sunda Wiwitan menjalankan kehidupan dengan terus menjaga dan merawat nilai nilai baik yang diajarkan oleh leluhur mereka” tuturnya.
Hak-hak Masyarakat Adat
Masyarakat Sunda Wiwitan Kuningan sudah ada sejak tahun 1840-an di daerah Cigugur yang menganut faham ajaran Madrais. Kepercayaan lokal tidak termasuk kedalam enam agama resmi menurut Undang-undang yang ditetapkan namun dalam kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah ditetapkan sebagai Penghayat. Indonesia sejak dulu memiliki agama asli nusantara yang terbentuk sebelum agama pendatang datang diantaranya yaitu Sunda Wiwitan, Kejawen, Djawa Sunda, Parmalim, Kaharingan dan lain sebagainya. Penduduk yang sampai saat ini masih menganut dan memegang teguh agama kepercayaan lokal disama ratakan dalam kolom KTP sebagai Penghayat.
“Setiap nama memiliki sejarah, esensi dan makna yang terkandung menjadi nilai utama. Sunda Wiwitan dan agama lokal lainnya memiliki esensinya masing masing yang menjadi ciri dari ajaran tersebut sehingga tidak bisa dipukul sama rata” ujarnya.
Masyarakat Adat Sunda Wiwitan hingga saat ini masih memperjuangkan kejelasan status hukum sebagai masyarakat adat. Hal tersebut dilakukan bukan untuk menambah jumlah agama yang sudah ada karena eksistensi Sunda Wiwitan sudah ada sebelum enam agama resmi masuk. “Penetapan kejelasan masyarakat adat sebagai wujud negara mengapresiasi keberadaan, keberagaman dan kebhinekaan berbangsa. Penetapan status hukum masyarakat adat juga sebagai salah satu upaya melindungi hidup dan menghidupi anak bumi Indonesia,” ujar Djuwita.
Istilah mayoritas dan minoritas menjadi sebuah dampak kebatinan beragama. Karena hal itu akan menjadi fokus pada kuantitas dibandingkan dengan kualitas.
“Seringkali ada istilah mayoritas melindungi minoritas, minoritas menghormati mayoritas. Bahasa itu salah seharusnya mayoritas terhadap minoritas menghormati dan sebaliknya minoritas terhadap mayoritas juga menghormati dan negara melindungi,” katanya.
Selama ada istilah mayoritas dan minoritas kita akan berkutat terus terhadap kuantitas jumlah umat yang harus dipertahankan atau bertambah.
Hingga saat ini penetapan masyarakat Sunda Wiwitan sebagai masyarakat adat belum bisa terwujud. Hal ini berkaitan dengan belum terpenuhinya persyaratan yang mengacu pada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) no 52 tahun 2014 mengenai Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Dudi Pahrudin yang ditemui di kantornya pada Senin (20/06) diakuinya sejak tahun 2020 Masyarakat AKUR sudah mengajukan permohonan pengajuan masyarakat adat. Namun setelah dilakukan penelitian dan menelaah lebih lanjut masyarakat Sunda Wiwitan kabupaten Kuningan belum memenuhi semua persyaratan.
Pengkajian dilakukan secara bertahap melalui proses identifikasi, verifikasi dan validasi melibatkan tim Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA) yang saat itu dibentuk setelah permohonan masuk.
“Ternyata setelah dilakukan beberapa kajian ini belum masuk memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam Permendagri no 52 tahun 2014, sehingga kami dari panitia PMHA mengajukan hasil kajian ke Bupati” Ujar kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
Diterangkannya kemudian, setelah Bupati Acep Purnama menerima hasil kajian dari DPMD, Bupati melalui surat keputusan langsung menyampaikan hasil bahwa belum memenuhi syarat untuk penetapan masyarakat adat.
“Pada sampai saat ini belum bisa menetapkan AKUR ini sebagai masyarakat hukum adat” ujarnya.
Penetapan masyarakat hukum adat sendiri memiliki parameter kriteria yang harus dipenuhi. Melalui temuan tim PMHA, Sunda Wiwitan AKUR tidak memenuhi aspek kriteria sebagai mana tertuang dalam Permendagri. Kelima hal itu yakni sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan, dan kelembagaan sistem adat.
Pemerintah selalu membuka ruang terhadap Sunda Wiwitan. Hal ini dibuktikan ketika permohonan pertama masuk pemda langsung bertindak membuat PMHA.
“Kita membuka ruang karena ada regulasinya, maka dibentuklah PMHA supaya jelas termasuk meminta bantuan kepada para ahli supaya lebih komprehensif” tuturnya. “Kecuali kalau misalnya ada ditemukan bukti baru, itu akan kita kaji ulang dan identifikasi kembali apakah sudah memenuhi kriteria untuk penetapan masyarakat hukum adat ” tandasnya
Respon Sunda Wiwitan
“Kita sudah melewati proses itu, semua persyaratan sudah kita sampaikan untuk dipertimbangkan, tetapi PMHA kami ditolak,” papar Djuwita
Menurutnya gambaran sebagian masyarakat atau para petinggi, masyarakat hukum adat adalah mereka tinggal di pegunungan, eksklusif terbelakang. Namun, masyarakat adat Sunda Wiwitan Cigugur berbeda. Jika meninjau latar belakang masyarakat AKUR memiliki tradisi yang secara turun temurun beregenerisasi. Tradisi tersebut merupakan nilai adat karuhun urang yang di pertahankan dalam proses kehidupan.
“Misal kita melanjutkan keyakinan para leluhur ajarannya yang kemudian diterapkan dalam sistem pernikahan, kelahiran sampai kematian” ungkapnya
Sambungnya kemudian, ciri ciri masyarakat adat yang bergotong royong bertahan dalam sebuah ikatan nilai sama sekali tidak dipertimbangkan. Penghayat hingga saat ini mampu bertahan dalam kehidupan yang plural dikatakan karena mempertahankan ketradisian dan keadatan.
Pengajuan Hukum Masyarakat Adat (PMHA) menurut Djuwita sudah dilakukan sejak 2014. Berbarengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Namun proses dinilai lamban dilakukan. “Setelah ada kasus penyegelan bakal makam pada 2020 semua mendorong untuk segera mengesahkan PMHA masyarakat hukum adat,” ungkapnya.
Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Sunda Wiwitan perlu dilakukan legalisasi dari pemerintah kabupaten Kuningan. Ketidakmauan pemerintah untuk melegalkan akan memberikan dampak hilangnya hak-hak selaku masyarakat adat, seperti pengambil alihan tanah adat.
“Ketika kita mengklaim bahwa tanah itu merupakan tanah warisan pangeran madrais untuk tidak diperjualbelikan dan untuk kemanfaatan masyarakat akhirnya itu jadi mentah,”.
Jelasnya lagi, konflik yang muncul kepermukaan terlihat seperi konflik internal. Padahal tanah peninggalan Pangeran Sadewa Madrais dan Tejabuana dalam amanatnya dan manuskrip tidak boleh dibagi wariskan dan diperjualbelikan. “Akan tetapi di pengadilan ketika PMHA kita Tidak diakui, mereka samar mengakui kita sebagai masyarakat adat yang memiliki tanah dan wilayah dan berdampak pada hak hak lainnya,” pungkasnya.
Ketidakmauan Pemerintah daerah untuk menetapkan masyarakat AKUR Cigugur sebagai bagian dari masyarakat adat merupakan bentuk diskriminasi terhadap bangsanya sendiri. Menurut Prof Sulistyowati Irianto seorang ahli hukum dan antropologi Universitas Indonesia (UI).
Dari sisi antropologi hukum, NKRI bukan satu-satunya nation, karena bangsa ini terdiri dari ratusan kesukubangsaan. Itulah yang di antaranya disebut sebagai masyarakat adat. Mereka ada dan berkembang dengan norma dan aturan adatnya masing-masing. Lalu, ketika Indonesia ada, mereka disuruh mendaftar dengan standar yang dibuat oleh negara.
“Jadi ini sebagai bentuk pengontrolan, terlebih di Orde Baru yang mengharuskan masyarakat adat menganut salah satu dari 5 agama resmi. Sehingga, adalah bentuk pembatasan hak dan diskriminasi ketika ada keharusan masyarakat adat untuk mendaftar atau mengajukan ke negara agar diakui dan terdaftar sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA),” ungkapnya.
Sementara kriteria-kriteria MHA tidak seluruhnya mengakomodir realitas masyarakat adat yang berbeda-beda.
Pertanyaannya, masyarakat adat harus mendaftar untuk kepentingan apa dan siapa?
Bukankah Konstitusi Republik Indonesia memberikan jaminan penghormatan (menghormati) terhadap kepercayaan setiap warga atau orang dan bagaimana mereka mengembangkan kebudayaan dan memperoleh hak hidup mereka masing-masing?
Faktanya, banyak ruang hidup masyarakat adat yang terus-menerus terampas, hilang. Orang Rimba Jambi, Tolotang, ratusan masyarakat adat di Papua, dan wilayah nusantara lainnya semakin terdesak dan banyak yang punah, tidak bertahan.
“Harusnya negara menghormati dan menjamin ruang hidup mereka, masyarakat adat, apa pun bentuknya dan sistemnya. Tanggung jawab negara adalah menghormati dan melindungi mereka untuk berkembang dengan cara mereka sendiri, dengan hukum (adat) mereka sendiri, tanpa batasan atau kriteria yang dibuat oleh negara,” jelasnya lagi
Masyarakat adat sudah ada jauh sebelum Indonesia hadir dan sudah berbaur dengan masyarakat lainnya, termasuk satu masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya.
Di perkotaan, faktanya banyak masyarakat adat yang tetap menjalankan kehidupan atau sistem adat mereka dan berjumpa dengan sistem masyarakat kota atau masyarakat adat lainnya yang hadir di wilayah tertentu.
“Adalah salah, jika negara menganggap sistem norma atau kepercayaan masyarakat adat harus tetap dan sama dari sejak kemunculannya. Justru, negara harus menghormati bentuk-bentuk kepercayaan setiap warga atau orang dan bagaimana mereka mengembangkan adat dan kebudayaan mereka, terutama memperoleh hak hidup mereka dengan sistem budayanya masing-masing. Konstitusi menjamin hal tersebut.”
Batu Satangtung
Batu satangtung adalah makam berupa susunan batu yang ditata berbetuk tugu memiliki dua liang lahat. Pembangunan makam dilakukan atas dasar permintaan pangeran Djatikusumah sebagai sesepuh masyarakat adat Sunda Wiwitan. Pada tahun 2019 pangeran Djatikusumah mengumpulkan putera puteri untuk berwasiat kelak ketika dirinya wafat dimakamkan pada tanah milik pribadi. Tanah tersebut kemudian diposisikan sebagai tanah komunitas di desa Cisantana.
Gambaran bakal makam tersebut dirancang sendiri oleh sesepuh Sunda Wiwitan yaitu dibuatkan tetengger atau simbol dalam bentuk batu satangtung yang digambarkan dan dikonstruksi sesuai keinginannya.
“Jadi dia secara detail menggambarkan tatanan teknis makamnya seperti apa, makna apa saja yang dilambangkan simbol batu satangtung sampai sedetail itu,” ujar Kang Dedi Ahimsa kepada NU Online Jabar.
Lanjutnya, gambaran bakal makam tersebut disetujui serta disanggupi oleh pihak keluarga. Hasil permintaan tersebut disepakati bersama dengan beberapa pengikut penghayat, warga Katolik dan muslim yang berdekatan dengan wilayah lokasi batu satangtung. Masyarakat bekerjasama dan gotong royong mempersiapkan lokasi makam semua agama yang berada dalam lingkungan membantu proses pembuatan makam batu satangtung.
“Beberapa komunitas Sunda wiwitan di Jawa Barat membantu membereskan tanah, angkat batu yang gede-gede yang diantaranya kemudian menjadi bahan dasar makam batu satangtung” tuturnya.
Beberapa bulan dari proses pembuatan batu satangtung muncul isu terkait Sunda Wiwitan sedang membangun pemujaan. Bakal makam dituduh berkamuflase sebagai makam leluhur yang kelak akan dijadikan area pemujaan. Maka kemudian, sebagian kelompok muslim Cisantana atau Cigugur melakukan audiensi kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuntut pembangunan dihentikan. Kelompok muslim tersebut beralasan batu satangtung akan menjadi tempat pemujaan yang bisa merusak akidah umat islam. Bupati Kuningan akhirnya menerbitkan instruksi melalui satpol PP untuk menghentikan pembangunan makam dengan alasan belum mendapatkan Izin mendirikan bangunan.
Ketika pembangunan dihentikan, pihak Sunda Wiwitan tidak menerima begitu saja, hal ini berkaitan dengan wasiat orang tua. Wasiat tersebut menjadi dasar alasan kenapa pembangunan harus dilanjutkan terlebih pembangunan berlokasi di tanah pribadi. Di lokasi sekitar bakal makam banyak ditemukan makam lain yang dilengkapi dengan simbol (tetengger) dan bangunan permanen lainnya.
“Berkaitan dengan alasan merusak akidah umat Islam itu tidak bisa menjadi alasan karena Sunda Wiwitan bukan Islam, apa yang mereka lakukan tidak ada kaitannya dengan merusak akidah umat Islam” katanya.
Ketika terjadi penolakan dari sebagian umat Islam pemerintah mengeluarkan instruksi untuk melakukan penyegelan. Bentuk perlawanan dilakukan Sunda Wiwitan dengan melakukan konferensi pers dan diskusi bahwa hal ini termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Melalui bebe beberapa dialog dan kegiatan yang difasilitasi oleh Dedi Ahimsa proses diskusi berlangsung.
“Melalui beberapa kegiatan diskusi dengan pihak Sunda wiwitan, MUI Cisantana dan pemerintah daerah terkait sudut pandang mereka” ujarnya
Setelah melalui beberapa obrolan segel penangguhan pembangunan dicabut dengan alasan sunda wiwitan sudah melengkapi persyaratan.
Menurut Dedy Ahimsa selaku orang yang pernah meneliti kehidupan beragama di Kecamatan Cigugur, sikap Intoleransi dikemudian hari dapat terjadi lagi berkaitan dengan Sunda Wiwitan.
Hal ini berkaitan dengan belum adanya penerimaan dari semua kelompok masyarakat Cisantana perihal pembukaan penyegelan batu satangtung. Dikhawatirkan ketika sesepuh masyarakat adat tutup usia dan dilakukan pemakaman disana terjadi penolakan kedua dan intoleransi terjadi kembali.
“Ini yang harus jadi perhatian pemerintah daerah, bahwa situasi yang tampak aman, damai, tentram, adalah semu. Itu yang saya khawatirkan” tuturnya.
Masyarakat kecamatan Cigugur yang plural dari segi keagamaan, identitas, kebudayaan bisa hidup berdampingan dengan memiliki ikatan sosial yang erat. Dapat saling menerima, mengakui, menghormati dapat menjadi pondasi yang kokoh dalam kehidupan masyarakat.
“Yang harus dilakukan pemerintah yaitu bagaimana ikatan sosial terbentuk yang disebut dengan kohesi sosial,” jelasnya. “Bagaimana pemerintah harus mewujudkan kohesi sosial di tengah masyarakat, salah satunya dengan memberi ruang agar masyarakat yang beragam ini dapat sering bertemu sehingga tidak sibuk dengan komunitasnya masing-masing,” pungkasnya
Eksekusi Tanah Adat
Kebaya putih membalut anggun perempuan yang berdiri tegak menyuarakan ketidakadilan. Megaphone di tangan melantangkan suaranya di hadapan polisi, wartawan, dan pemangku kebijakan. Di belakangnya berdiri perempuan-perempuan penghayat memakai kebaya serupa, laki-laki memakai baju kampret, dan barisan mahasiswa.
“Unjuk rasa yang kita lakukan saat ini adalah untuk menolak represi, menolak pembacaan keputusan eksekusi,” lantang Juwita.
Eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kuningan dengan Surat No.W.11.U16/825/HK.02/4/2022 memerintahkan pelaksanaan pencocokan (Constatering) dan sita eksekusi tanah adat Mayasih.
Dalam orasi yang disampaikan pada 18 Mei 2022 Juwita menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini harus dilakukan secara adat, karena tanah ini adalah tanah adat. Menurutnya banyak pihak yang tidak tahu mengenai persengketaan tanah adat yang terjadi.
“Banyak yang tidak tahu di balik persengketaan tanah ini. Ini bukan tanah waris,” tegasnya. “Ada amanat yang tertulis yang diamanati pangeran Tedja Buana, bahwa seluruh tanah dan bangunan diperuntukkan untuk kepentingan bersama,”.
Tanah adat yang berada di kawasan desa Cigugur bukanlah tanah kelompok. Ini tanah yang tidak bisa dibagi waris. Kawasan tanah adat diperuntukkan untuk kepentingan bersama menjadi tempat pelestarian budaya dan tradisi.
“Ketika eksekusi ini terus dilaksanakan berarti menjarah dan membunuh kebudayaan. Bagaimana hutang kita terhadap peradaban ke depan?” lantangnya menyisakan tanya.
Sri Melynda, kontributor NU Online Jabar di Kuningan, peraih Beasiswa Story Grant Liputan Keberagaman yang diadakan oleh SEJUK
https://jabar.nu.or.id/ngalogat/mengenal-dan-memahami-sunda-wiwitan-cigugur-3zjGz