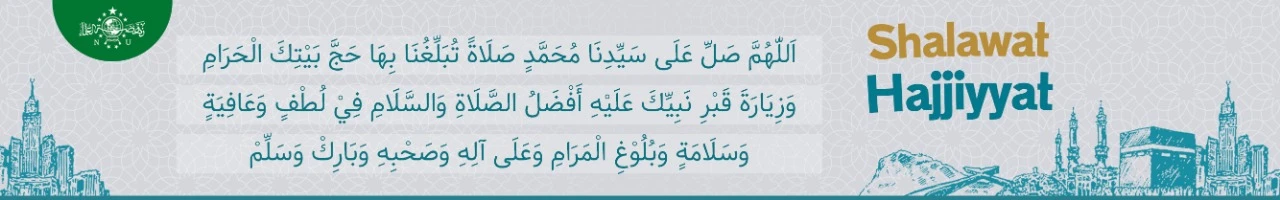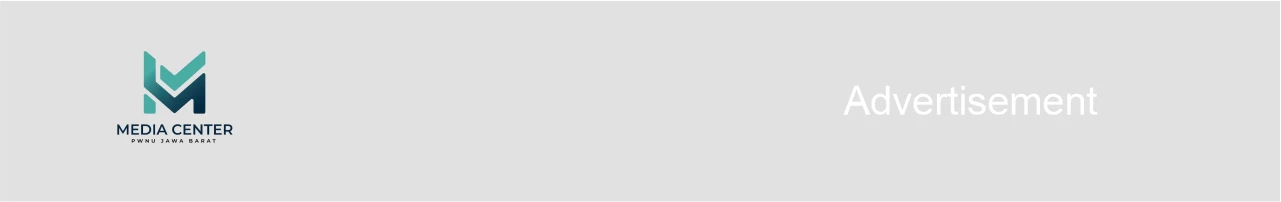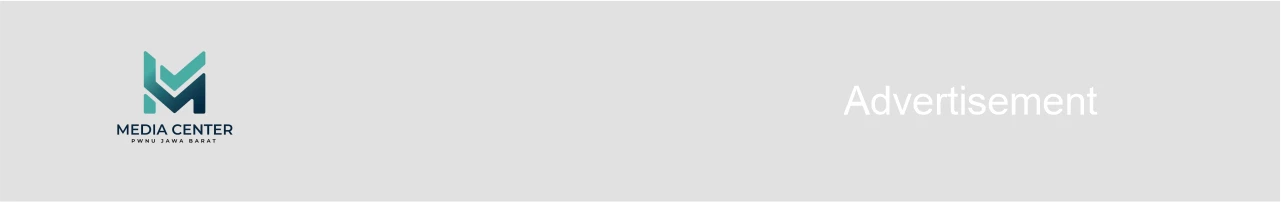Syekh Syihabuddin Ahmad ibn Salamah al-Qalyubi didalam karyanya yakni kitab An-Nawâdir bahwa pada suatu kesempatan Abu Yusuf Ya’qub bin Yusuf bercerita tentang salah seorang sahabatnya yang unik. Ia merupakan orang yang wara’ dan takwa meski orang-orang mengenal karibnya itu sebagai orang fasik dan pendosa.
Bahkan, sudah dua puluh tahun Abu Yusuf melakukan tawaf di sekitar Ka’bah bersamanya. Tidak seperti Abu Yusuf yang berpuasa terus menerus (dawâm), salah satu sahabatnya ini melaksanakan puasa tersebut dengan teknis sehari puasa dan sehari selanjutnya berbuka.
Ketika memasuki 10 hari bulan Dzulhijjah, sahabat Abu Yusuf ini menunaikan puasa secara sempurna kendati ia berada di padang sahara yang tandus. Bersama Abu Yusuf, ia masuk kota Thurthus dan menetap di sana untuk beberapa lama. Di tempat gersang inilah, persisnya di sebuah kawasan reruntuhan bangunan, ia wafat tanpa seorang pun yang tahu kecuali Abu Yusuf.
Abu Yusuf pun keluar mencari kain kafan dan alangkah kagetnya tatkala dirinya kembali menyaksikan kerumunan orang berkunjung, mengafani, sekaligus menyalati jenazah sahabatnya tersebut di tempat yang semula tak berpenghuni. Karena begitu ramainya, Abu Yusuf sampai tak bisa masuk lokasi reruntuhan bangunan itu.
Para pelayat menyebut-nyebut almarhum sebagai orang yang zuhud dan termasuk dari kekasih Allah (waliyyullah).
“Subhanallah, siapa yang mengumumkan kematiannya hingga orang-orang berbondong-bondong bertakziah, menyalati, dan menangisi kepergiannya?” tanya Abu Yusuf dengan heran.
Setelah melalui perjuangan keras, akhirnya Abu Yusuf mampu berhasil mendekati jenazah sahabatnya tersebut dan terperanjat saat melihat kain kafan yang tak biasa. Pada kain itu tercantum tulisan berwarna hijau:
هذا جزاء من آثر رضا الله على رضا نفسه وأحب لقاءنا فأحببنا لقاءه
“Inilah balasan orang yang mengutamakan ridha Allah ketimbang ridha dirinya sendiri; orang yang rindu menemui-Ku dan karenanya Aku pun rindu menemuinya.”
Pasca shalat jenazah dan menguburkan telah selesai dilakukan, rasa kantuk berat menghampiri Abu Yusuf hingga akhirnya tertidur. Di dunia mimpi inilah Abu Yusuf menyaksikan sahabatnya yang ahli puasa tersebut menunggang kuda hijau serta berpakaian hijau dengan sebuah bendera di tangannya. Di belakangnya ada seorang pemuda tampan berbau harum. Di belakang pemuda ini, ada dua orang tua diikuti di belangnya lagi satu orang tua dan satu pemuda.
“Siapa mereka?” Tanya Abu Yusuf.
“Pemuda tampan itu adalah Nabi kita Muhammad shallallâhu ‘alaihi wasallam. Dua orang tua itu adalah Abu Bakar dan Umar, sementara orang tua dan pemuda itu adalah Utsman dan Ali. Dan akulah pemegang bendera di depan mereka,” jelas almarhum sahabatnya dalam mimpi itu.
“Hendak ke manakah mereka?”
“Mereka ingin meziarahiku.”
Abu Yusuf pun kagum, “Bagaimana kau bisa mendapatkan kemuliaan semacam ini?”
“Sebab aku memprioritaskan ridha Allah dibanding ridha diriku sendiri dan aku berpuasa pada 10 hari Dzulhijjah,” jawab sahabatnya.
Abu Yusuf pun bangun dari tidur, lalu sejak itu ia tak pernah meninggalkan amalan puasa itu hingga akhir hayat.
Anjuran memperbanyak amal saleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah termaktub dalam beberapa hadits. Misalnya hadits riwayat Ibnu ‘Abbas yang ada di dalam Sunan At-Tirmidzi yang mengatakan, “Tiada ada hari lain yang disukai Allah SWT untuk beribadah seperti sepuluh hari ini (Dzulhijjah).”
Meski diatas disebutkan kata “sepuluh hari”, puasa jika dimulai 1 Dzulhijjah cukup dijalankan sembilan hari karena tanggal 10 Dzulhijjah (juga hari tasyriq: 11, 12, 13 Dzulhijjah) adalah hari terlarang untuk berpuasa. Sebagaimana pendapat Imam An-Nawawi yang dikutip dari Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadzi bahwa yang dimaksud dengan ayyamul ‘asyr (10 hari) adalah 9 hari sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Wallahu a’lam. (Muhammad Rizqy Fauzi).
Tulisan ini bersumber dari NU Online yang diterbitkan pada September 2016. Kami merilis kembali dengan perubahan beberapa struktur pada judul dan narasinya